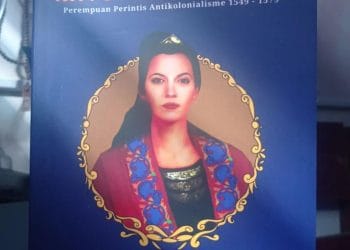|
| Ilustrasi Gus Mus bersama Mbah Moen/ @islamsantuy |
Oleh KH Yahya Cholil Staquf
“Abahmu pernah rasan-rasan,
kepingin merenovasi langggar”, kata paman saya, Kyai Mustofa Bisri, “tapi
sampai meninggalnya belum kesampaian”.
Saya tercenung. Itu bukan
kalimat sharih, tapi mafhumnya jelas: perintah. Dan perintah yang musykil.
Betapa tidak? Saya tidak punya uang. Dan saya bukan profesional dalam bidang
tertentu yang dapat menghasilkan uang –saya baru saja “memensiunkan diri” dari
profesi politik dan belum menemukan profesi penggantinya.
Hanyut dalam cara berpikir
yang “normal” dari seorang “gus kontemporer” seperti saya, segera muncul dalam
benak saya gagasan untuk mencari bantuan dari sumber-sumber yang paling populer
di kalangan pondok pesantren dewasa ini, yaitu para aktor pemangku kepentingan
politik, khususnya pejabat-pejabat pemerintahan. Dan saya merasa punya
keunggulan dalam hal itu, mengingat saya pernah aktif dalam politik hingga ke
puncak arena permainannya (menjadi Juru Bicara Presiden).
Maka segera pulalah saya
kerjakan persiapan yang lazim: menyusun proposal dan surat permohonan bantuan
dengan alamat kontak-kontak politik yang saya miliki di kalangan pejabat
pemerintahan. Di bagian bawah proposal dan surat-surat permohonan itu saya
sediakan ruang untuk tanda tangan paman saya: K.H. A. Mustofa Bisri. Pikir
saya, ketokohan paman saya jelas punya harga mahal untuk “dijual”. Saya suruh
salah seorang sepupu yang telah saya tunjuk sebagai Ketua Panitia untuk
menindaklanjuti dokumen-dokumen itu, termasuk meminta tanda tangan dari paman
saya kemudian mengirim ke alamat-alamat yang telah saya tentukan daftarnya.
Satu-dua hari tanpa
laporan, saya pikir urusan sudah beres. Tinggal tunggu jawaban. Yang datang
kemudian adalah undangan untuk “berkumpul di rumah paman saya” selepas ‘isya.
Tak ada informasi untuk keperluan apa. Saya hanya menduga, paman saya hendak
mengadakan manakiban untuk suatu hajat tertentu, entah apa.
Agak terlambat saya datang,
di ruang tamu telah hadir kyai-kyai dan ustadz-ustadz yang mengajar di
pesantren kami, beserta seluruh jajaran Pengurus Pondok, lengkap. Paman saya
sendiri belum keluar. Saya segera merasa aneh ketika saya dapati, tak seorang
pun yang hadir mengetahui keperluan pertemuan malam itu. Tak ada pula
suguhan-suguhan khusus seperti lazimnya orang punya hajat. Sepupu saya, Si
Ketua Panitia, yang ditugasi menyampaikan undangan pertemuan, hanya
“embah-embuh”. Malah bolak-balik keluar-masuk ruangan, seperti sibuk ini-itu,
tapi tak jelas urusannya. Sejurus-dua-jurus kami menunggu, barulah paman saya
muncul. Perasaan aneh menghebat, diikuti ketegangan, melihat raut muka paman
saya tidak seperti biasanya. Setahu saya, paman saya senantiasa memperlihatkan
wajah cerah setiap menemui tamu. Kecuali malam itu. Wajahnya muram. Jelas-jelas
menampakkan kegusaran. Semua yang hadir menyadari ketidaklaziman itu sehingga
ketegangan pun merata.
Setelah duduk, tanpa
didahului basa-basi maupun bacaan fatihah untuk membuka pertemuan, paman saya
langsung meluncurkan kalimat-kalimat tajam, jelas-jelas ditujukan kepada saya.
Seandainya saya tidak mengenal beliau, pasti saya ketakutan setengah mati.
Ketakutan yang jelas tampak pada wajah-wajah mereka yang hadir. Seorang
pengurus pondok bahkan kelihatan amat menderita karena ngampet semaput.
Tapi saya kenal betul paman
saya ini. Saya sudah hafal segala kasih-sayangnya. Maka yang lantas mengembang
di hati saya adalah gairah belajar yang khusyu’.
“Jangan sembarangan mencari
uang!” kata paman saya. Iramanya datar, tapi nadanya tajam menusuk. Semua orang
menunduk.
“Kalau cuma pengen bangunan
pondok yang bagus-bagus, ngapain nunggu awakmu?” kata beliau lagi, “apa dikira
yang punya kenalan pejabat-pejabat di sini baru awakmu? Abahmu dan embahmu
tidak? Kalau mau uangnya pejabat, dari dulu juga bisa!”
Terus terang, saya
tercekat. Yang ini melubangi jantung saya betul. Embah saya, Kyai Bisri Mustofa,
adalah syuriyah NU dan anggota Konstituante, kemudian anggota MPR hingga
meninggalnya; ayah saya, Kyai Cholil Bisri, Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB dan
Wakil Ketua MPR RI hingga meninggalnya; saya cuma kecoak dihadapan mereka. Saya
kian tunduk melipat punggung. Ruangan membeku. Pikiran saya galau. Tak sempat
lagi saya mengingat untuk mengecek, apakah pengurus pondok yang tadi itu sudah
semaput atau belum.
“Teman-teman itu sendiri
(maksud saya, pejabat-pejabat itu) yang menawari kok, Paklik”, saya nyeletuk.
Suara saya mengambang. Tak jelas tujuannya. Mungkin sekedar usaha mencairkan
kebekuan. Tapi sia-sia.
“Mereka menawari karena
punya kepentingan!” sergah paman saya. Saya kehilangan semua kata-kata.
“Embahmu dan abahmu tidak
pernah mementingkan bangunan”, beliau melanjutkan, “yang penting barokah. Jadi,
hati-hatilah mencari uang. Tak ada gunanya punya macam-macam kalau tidak
barokah”.
Paman saya merogoh saku.
“Nih”, katanya, lalu
menyodorkan sebuah buku kecil: buku tabungan, “itu uangku sendiri, kucari-cari
sendiri, kukumpul-kumpulkan sendiri. Halal. Pakai itu!”
Paman saya berdiri,
menyingkap gorden pembatas ruang tamu lebar-lebar. Dibalik gorden itu meja makan
penuh hidangan.
“Ayo makan! Makan!”
Saya pastikan, semua orang
menghela napas lega. Saya intip buku tabungan itu, isinya 150 juta rupiah. Saya
menelan ludah. Perkiraan ongkos bangunan yang akan saya bikin mencapai lebih
dari 800 juta. Ya sudahlah, pikir saya, bagaimana nanti saja. []
 |
| Ilustrasi Gus Mus bersama Mbah Moen/ @islamsantuy |
Oleh KH Yahya Cholil Staquf
“Abahmu pernah rasan-rasan,
kepingin merenovasi langggar”, kata paman saya, Kyai Mustofa Bisri, “tapi
sampai meninggalnya belum kesampaian”.
Saya tercenung. Itu bukan
kalimat sharih, tapi mafhumnya jelas: perintah. Dan perintah yang musykil.
Betapa tidak? Saya tidak punya uang. Dan saya bukan profesional dalam bidang
tertentu yang dapat menghasilkan uang –saya baru saja “memensiunkan diri” dari
profesi politik dan belum menemukan profesi penggantinya.
Hanyut dalam cara berpikir
yang “normal” dari seorang “gus kontemporer” seperti saya, segera muncul dalam
benak saya gagasan untuk mencari bantuan dari sumber-sumber yang paling populer
di kalangan pondok pesantren dewasa ini, yaitu para aktor pemangku kepentingan
politik, khususnya pejabat-pejabat pemerintahan. Dan saya merasa punya
keunggulan dalam hal itu, mengingat saya pernah aktif dalam politik hingga ke
puncak arena permainannya (menjadi Juru Bicara Presiden).
Maka segera pulalah saya
kerjakan persiapan yang lazim: menyusun proposal dan surat permohonan bantuan
dengan alamat kontak-kontak politik yang saya miliki di kalangan pejabat
pemerintahan. Di bagian bawah proposal dan surat-surat permohonan itu saya
sediakan ruang untuk tanda tangan paman saya: K.H. A. Mustofa Bisri. Pikir
saya, ketokohan paman saya jelas punya harga mahal untuk “dijual”. Saya suruh
salah seorang sepupu yang telah saya tunjuk sebagai Ketua Panitia untuk
menindaklanjuti dokumen-dokumen itu, termasuk meminta tanda tangan dari paman
saya kemudian mengirim ke alamat-alamat yang telah saya tentukan daftarnya.
Satu-dua hari tanpa
laporan, saya pikir urusan sudah beres. Tinggal tunggu jawaban. Yang datang
kemudian adalah undangan untuk “berkumpul di rumah paman saya” selepas ‘isya.
Tak ada informasi untuk keperluan apa. Saya hanya menduga, paman saya hendak
mengadakan manakiban untuk suatu hajat tertentu, entah apa.
Agak terlambat saya datang,
di ruang tamu telah hadir kyai-kyai dan ustadz-ustadz yang mengajar di
pesantren kami, beserta seluruh jajaran Pengurus Pondok, lengkap. Paman saya
sendiri belum keluar. Saya segera merasa aneh ketika saya dapati, tak seorang
pun yang hadir mengetahui keperluan pertemuan malam itu. Tak ada pula
suguhan-suguhan khusus seperti lazimnya orang punya hajat. Sepupu saya, Si
Ketua Panitia, yang ditugasi menyampaikan undangan pertemuan, hanya
“embah-embuh”. Malah bolak-balik keluar-masuk ruangan, seperti sibuk ini-itu,
tapi tak jelas urusannya. Sejurus-dua-jurus kami menunggu, barulah paman saya
muncul. Perasaan aneh menghebat, diikuti ketegangan, melihat raut muka paman
saya tidak seperti biasanya. Setahu saya, paman saya senantiasa memperlihatkan
wajah cerah setiap menemui tamu. Kecuali malam itu. Wajahnya muram. Jelas-jelas
menampakkan kegusaran. Semua yang hadir menyadari ketidaklaziman itu sehingga
ketegangan pun merata.
Setelah duduk, tanpa
didahului basa-basi maupun bacaan fatihah untuk membuka pertemuan, paman saya
langsung meluncurkan kalimat-kalimat tajam, jelas-jelas ditujukan kepada saya.
Seandainya saya tidak mengenal beliau, pasti saya ketakutan setengah mati.
Ketakutan yang jelas tampak pada wajah-wajah mereka yang hadir. Seorang
pengurus pondok bahkan kelihatan amat menderita karena ngampet semaput.
Tapi saya kenal betul paman
saya ini. Saya sudah hafal segala kasih-sayangnya. Maka yang lantas mengembang
di hati saya adalah gairah belajar yang khusyu’.
“Jangan sembarangan mencari
uang!” kata paman saya. Iramanya datar, tapi nadanya tajam menusuk. Semua orang
menunduk.
“Kalau cuma pengen bangunan
pondok yang bagus-bagus, ngapain nunggu awakmu?” kata beliau lagi, “apa dikira
yang punya kenalan pejabat-pejabat di sini baru awakmu? Abahmu dan embahmu
tidak? Kalau mau uangnya pejabat, dari dulu juga bisa!”
Terus terang, saya
tercekat. Yang ini melubangi jantung saya betul. Embah saya, Kyai Bisri Mustofa,
adalah syuriyah NU dan anggota Konstituante, kemudian anggota MPR hingga
meninggalnya; ayah saya, Kyai Cholil Bisri, Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB dan
Wakil Ketua MPR RI hingga meninggalnya; saya cuma kecoak dihadapan mereka. Saya
kian tunduk melipat punggung. Ruangan membeku. Pikiran saya galau. Tak sempat
lagi saya mengingat untuk mengecek, apakah pengurus pondok yang tadi itu sudah
semaput atau belum.
“Teman-teman itu sendiri
(maksud saya, pejabat-pejabat itu) yang menawari kok, Paklik”, saya nyeletuk.
Suara saya mengambang. Tak jelas tujuannya. Mungkin sekedar usaha mencairkan
kebekuan. Tapi sia-sia.
“Mereka menawari karena
punya kepentingan!” sergah paman saya. Saya kehilangan semua kata-kata.
“Embahmu dan abahmu tidak
pernah mementingkan bangunan”, beliau melanjutkan, “yang penting barokah. Jadi,
hati-hatilah mencari uang. Tak ada gunanya punya macam-macam kalau tidak
barokah”.
Paman saya merogoh saku.
“Nih”, katanya, lalu
menyodorkan sebuah buku kecil: buku tabungan, “itu uangku sendiri, kucari-cari
sendiri, kukumpul-kumpulkan sendiri. Halal. Pakai itu!”
Paman saya berdiri,
menyingkap gorden pembatas ruang tamu lebar-lebar. Dibalik gorden itu meja makan
penuh hidangan.
“Ayo makan! Makan!”
Saya pastikan, semua orang
menghela napas lega. Saya intip buku tabungan itu, isinya 150 juta rupiah. Saya
menelan ludah. Perkiraan ongkos bangunan yang akan saya bikin mencapai lebih
dari 800 juta. Ya sudahlah, pikir saya, bagaimana nanti saja. []
 |
| Ilustrasi Gus Mus bersama Mbah Moen/ @islamsantuy |
Oleh KH Yahya Cholil Staquf
“Abahmu pernah rasan-rasan,
kepingin merenovasi langggar”, kata paman saya, Kyai Mustofa Bisri, “tapi
sampai meninggalnya belum kesampaian”.
Saya tercenung. Itu bukan
kalimat sharih, tapi mafhumnya jelas: perintah. Dan perintah yang musykil.
Betapa tidak? Saya tidak punya uang. Dan saya bukan profesional dalam bidang
tertentu yang dapat menghasilkan uang –saya baru saja “memensiunkan diri” dari
profesi politik dan belum menemukan profesi penggantinya.
Hanyut dalam cara berpikir
yang “normal” dari seorang “gus kontemporer” seperti saya, segera muncul dalam
benak saya gagasan untuk mencari bantuan dari sumber-sumber yang paling populer
di kalangan pondok pesantren dewasa ini, yaitu para aktor pemangku kepentingan
politik, khususnya pejabat-pejabat pemerintahan. Dan saya merasa punya
keunggulan dalam hal itu, mengingat saya pernah aktif dalam politik hingga ke
puncak arena permainannya (menjadi Juru Bicara Presiden).
Maka segera pulalah saya
kerjakan persiapan yang lazim: menyusun proposal dan surat permohonan bantuan
dengan alamat kontak-kontak politik yang saya miliki di kalangan pejabat
pemerintahan. Di bagian bawah proposal dan surat-surat permohonan itu saya
sediakan ruang untuk tanda tangan paman saya: K.H. A. Mustofa Bisri. Pikir
saya, ketokohan paman saya jelas punya harga mahal untuk “dijual”. Saya suruh
salah seorang sepupu yang telah saya tunjuk sebagai Ketua Panitia untuk
menindaklanjuti dokumen-dokumen itu, termasuk meminta tanda tangan dari paman
saya kemudian mengirim ke alamat-alamat yang telah saya tentukan daftarnya.
Satu-dua hari tanpa
laporan, saya pikir urusan sudah beres. Tinggal tunggu jawaban. Yang datang
kemudian adalah undangan untuk “berkumpul di rumah paman saya” selepas ‘isya.
Tak ada informasi untuk keperluan apa. Saya hanya menduga, paman saya hendak
mengadakan manakiban untuk suatu hajat tertentu, entah apa.
Agak terlambat saya datang,
di ruang tamu telah hadir kyai-kyai dan ustadz-ustadz yang mengajar di
pesantren kami, beserta seluruh jajaran Pengurus Pondok, lengkap. Paman saya
sendiri belum keluar. Saya segera merasa aneh ketika saya dapati, tak seorang
pun yang hadir mengetahui keperluan pertemuan malam itu. Tak ada pula
suguhan-suguhan khusus seperti lazimnya orang punya hajat. Sepupu saya, Si
Ketua Panitia, yang ditugasi menyampaikan undangan pertemuan, hanya
“embah-embuh”. Malah bolak-balik keluar-masuk ruangan, seperti sibuk ini-itu,
tapi tak jelas urusannya. Sejurus-dua-jurus kami menunggu, barulah paman saya
muncul. Perasaan aneh menghebat, diikuti ketegangan, melihat raut muka paman
saya tidak seperti biasanya. Setahu saya, paman saya senantiasa memperlihatkan
wajah cerah setiap menemui tamu. Kecuali malam itu. Wajahnya muram. Jelas-jelas
menampakkan kegusaran. Semua yang hadir menyadari ketidaklaziman itu sehingga
ketegangan pun merata.
Setelah duduk, tanpa
didahului basa-basi maupun bacaan fatihah untuk membuka pertemuan, paman saya
langsung meluncurkan kalimat-kalimat tajam, jelas-jelas ditujukan kepada saya.
Seandainya saya tidak mengenal beliau, pasti saya ketakutan setengah mati.
Ketakutan yang jelas tampak pada wajah-wajah mereka yang hadir. Seorang
pengurus pondok bahkan kelihatan amat menderita karena ngampet semaput.
Tapi saya kenal betul paman
saya ini. Saya sudah hafal segala kasih-sayangnya. Maka yang lantas mengembang
di hati saya adalah gairah belajar yang khusyu’.
“Jangan sembarangan mencari
uang!” kata paman saya. Iramanya datar, tapi nadanya tajam menusuk. Semua orang
menunduk.
“Kalau cuma pengen bangunan
pondok yang bagus-bagus, ngapain nunggu awakmu?” kata beliau lagi, “apa dikira
yang punya kenalan pejabat-pejabat di sini baru awakmu? Abahmu dan embahmu
tidak? Kalau mau uangnya pejabat, dari dulu juga bisa!”
Terus terang, saya
tercekat. Yang ini melubangi jantung saya betul. Embah saya, Kyai Bisri Mustofa,
adalah syuriyah NU dan anggota Konstituante, kemudian anggota MPR hingga
meninggalnya; ayah saya, Kyai Cholil Bisri, Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB dan
Wakil Ketua MPR RI hingga meninggalnya; saya cuma kecoak dihadapan mereka. Saya
kian tunduk melipat punggung. Ruangan membeku. Pikiran saya galau. Tak sempat
lagi saya mengingat untuk mengecek, apakah pengurus pondok yang tadi itu sudah
semaput atau belum.
“Teman-teman itu sendiri
(maksud saya, pejabat-pejabat itu) yang menawari kok, Paklik”, saya nyeletuk.
Suara saya mengambang. Tak jelas tujuannya. Mungkin sekedar usaha mencairkan
kebekuan. Tapi sia-sia.
“Mereka menawari karena
punya kepentingan!” sergah paman saya. Saya kehilangan semua kata-kata.
“Embahmu dan abahmu tidak
pernah mementingkan bangunan”, beliau melanjutkan, “yang penting barokah. Jadi,
hati-hatilah mencari uang. Tak ada gunanya punya macam-macam kalau tidak
barokah”.
Paman saya merogoh saku.
“Nih”, katanya, lalu
menyodorkan sebuah buku kecil: buku tabungan, “itu uangku sendiri, kucari-cari
sendiri, kukumpul-kumpulkan sendiri. Halal. Pakai itu!”
Paman saya berdiri,
menyingkap gorden pembatas ruang tamu lebar-lebar. Dibalik gorden itu meja makan
penuh hidangan.
“Ayo makan! Makan!”
Saya pastikan, semua orang
menghela napas lega. Saya intip buku tabungan itu, isinya 150 juta rupiah. Saya
menelan ludah. Perkiraan ongkos bangunan yang akan saya bikin mencapai lebih
dari 800 juta. Ya sudahlah, pikir saya, bagaimana nanti saja. []
 |
| Ilustrasi Gus Mus bersama Mbah Moen/ @islamsantuy |
Oleh KH Yahya Cholil Staquf
“Abahmu pernah rasan-rasan,
kepingin merenovasi langggar”, kata paman saya, Kyai Mustofa Bisri, “tapi
sampai meninggalnya belum kesampaian”.
Saya tercenung. Itu bukan
kalimat sharih, tapi mafhumnya jelas: perintah. Dan perintah yang musykil.
Betapa tidak? Saya tidak punya uang. Dan saya bukan profesional dalam bidang
tertentu yang dapat menghasilkan uang –saya baru saja “memensiunkan diri” dari
profesi politik dan belum menemukan profesi penggantinya.
Hanyut dalam cara berpikir
yang “normal” dari seorang “gus kontemporer” seperti saya, segera muncul dalam
benak saya gagasan untuk mencari bantuan dari sumber-sumber yang paling populer
di kalangan pondok pesantren dewasa ini, yaitu para aktor pemangku kepentingan
politik, khususnya pejabat-pejabat pemerintahan. Dan saya merasa punya
keunggulan dalam hal itu, mengingat saya pernah aktif dalam politik hingga ke
puncak arena permainannya (menjadi Juru Bicara Presiden).
Maka segera pulalah saya
kerjakan persiapan yang lazim: menyusun proposal dan surat permohonan bantuan
dengan alamat kontak-kontak politik yang saya miliki di kalangan pejabat
pemerintahan. Di bagian bawah proposal dan surat-surat permohonan itu saya
sediakan ruang untuk tanda tangan paman saya: K.H. A. Mustofa Bisri. Pikir
saya, ketokohan paman saya jelas punya harga mahal untuk “dijual”. Saya suruh
salah seorang sepupu yang telah saya tunjuk sebagai Ketua Panitia untuk
menindaklanjuti dokumen-dokumen itu, termasuk meminta tanda tangan dari paman
saya kemudian mengirim ke alamat-alamat yang telah saya tentukan daftarnya.
Satu-dua hari tanpa
laporan, saya pikir urusan sudah beres. Tinggal tunggu jawaban. Yang datang
kemudian adalah undangan untuk “berkumpul di rumah paman saya” selepas ‘isya.
Tak ada informasi untuk keperluan apa. Saya hanya menduga, paman saya hendak
mengadakan manakiban untuk suatu hajat tertentu, entah apa.
Agak terlambat saya datang,
di ruang tamu telah hadir kyai-kyai dan ustadz-ustadz yang mengajar di
pesantren kami, beserta seluruh jajaran Pengurus Pondok, lengkap. Paman saya
sendiri belum keluar. Saya segera merasa aneh ketika saya dapati, tak seorang
pun yang hadir mengetahui keperluan pertemuan malam itu. Tak ada pula
suguhan-suguhan khusus seperti lazimnya orang punya hajat. Sepupu saya, Si
Ketua Panitia, yang ditugasi menyampaikan undangan pertemuan, hanya
“embah-embuh”. Malah bolak-balik keluar-masuk ruangan, seperti sibuk ini-itu,
tapi tak jelas urusannya. Sejurus-dua-jurus kami menunggu, barulah paman saya
muncul. Perasaan aneh menghebat, diikuti ketegangan, melihat raut muka paman
saya tidak seperti biasanya. Setahu saya, paman saya senantiasa memperlihatkan
wajah cerah setiap menemui tamu. Kecuali malam itu. Wajahnya muram. Jelas-jelas
menampakkan kegusaran. Semua yang hadir menyadari ketidaklaziman itu sehingga
ketegangan pun merata.
Setelah duduk, tanpa
didahului basa-basi maupun bacaan fatihah untuk membuka pertemuan, paman saya
langsung meluncurkan kalimat-kalimat tajam, jelas-jelas ditujukan kepada saya.
Seandainya saya tidak mengenal beliau, pasti saya ketakutan setengah mati.
Ketakutan yang jelas tampak pada wajah-wajah mereka yang hadir. Seorang
pengurus pondok bahkan kelihatan amat menderita karena ngampet semaput.
Tapi saya kenal betul paman
saya ini. Saya sudah hafal segala kasih-sayangnya. Maka yang lantas mengembang
di hati saya adalah gairah belajar yang khusyu’.
“Jangan sembarangan mencari
uang!” kata paman saya. Iramanya datar, tapi nadanya tajam menusuk. Semua orang
menunduk.
“Kalau cuma pengen bangunan
pondok yang bagus-bagus, ngapain nunggu awakmu?” kata beliau lagi, “apa dikira
yang punya kenalan pejabat-pejabat di sini baru awakmu? Abahmu dan embahmu
tidak? Kalau mau uangnya pejabat, dari dulu juga bisa!”
Terus terang, saya
tercekat. Yang ini melubangi jantung saya betul. Embah saya, Kyai Bisri Mustofa,
adalah syuriyah NU dan anggota Konstituante, kemudian anggota MPR hingga
meninggalnya; ayah saya, Kyai Cholil Bisri, Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB dan
Wakil Ketua MPR RI hingga meninggalnya; saya cuma kecoak dihadapan mereka. Saya
kian tunduk melipat punggung. Ruangan membeku. Pikiran saya galau. Tak sempat
lagi saya mengingat untuk mengecek, apakah pengurus pondok yang tadi itu sudah
semaput atau belum.
“Teman-teman itu sendiri
(maksud saya, pejabat-pejabat itu) yang menawari kok, Paklik”, saya nyeletuk.
Suara saya mengambang. Tak jelas tujuannya. Mungkin sekedar usaha mencairkan
kebekuan. Tapi sia-sia.
“Mereka menawari karena
punya kepentingan!” sergah paman saya. Saya kehilangan semua kata-kata.
“Embahmu dan abahmu tidak
pernah mementingkan bangunan”, beliau melanjutkan, “yang penting barokah. Jadi,
hati-hatilah mencari uang. Tak ada gunanya punya macam-macam kalau tidak
barokah”.
Paman saya merogoh saku.
“Nih”, katanya, lalu
menyodorkan sebuah buku kecil: buku tabungan, “itu uangku sendiri, kucari-cari
sendiri, kukumpul-kumpulkan sendiri. Halal. Pakai itu!”
Paman saya berdiri,
menyingkap gorden pembatas ruang tamu lebar-lebar. Dibalik gorden itu meja makan
penuh hidangan.
“Ayo makan! Makan!”
Saya pastikan, semua orang
menghela napas lega. Saya intip buku tabungan itu, isinya 150 juta rupiah. Saya
menelan ludah. Perkiraan ongkos bangunan yang akan saya bikin mencapai lebih
dari 800 juta. Ya sudahlah, pikir saya, bagaimana nanti saja. []